KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang masih
memberikan kesehatan dan kesempatannya kepada kami semua. Sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah ini.
Berikut ini, kami persembahkan sebuah makalah (karya tulis)
yang berjudul Etnisitas Dalam Pembentukan “Nation and Character Building”. Kami
mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, terutama bagi
kami. Kepada pembaca yang budiman, jika terdapat kekurangan atau kekeliruan
dalam makalah ini, kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar.
Dengan selesainya makalah ini, kami mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Pendidikan IPS 1`. Semoga Allah
memberkahi makalah ini sehingga dapat benar-benar bermanfaat.
Sukabumi, Oktober
2012
Penyusun
DAFTAR ISI
Cover………………………………………………………………………………………………1
Kata
Pengatar……………………………………………………………………….……………..2
Daftar
Isi…………………………………………………………………………………………..3
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang……….……………………………………………………………………4
1.2
Rumusan Masalah……………………………………………………..............................5
1.3
Tujuan Makalah…………………………………………………………………………...5
1.4
Sistematika Penulisan……………………………………………………………………..5
BAB II TINJAUAN
PUSTAKA
2.1 Pengertian etnis, etnisasi dan ‘nation and character
building’……………………………..6
BAB
III PEMBAHASAN
3.1 Pengaruh barat dan kebudayaan Nasional.…………………...............................................7
3.2 Hubungan antara manusia, masyarakat, dan
kebudayaan.……………..…………………..8
3.3 Makna pengabdian……………………………………...………………………….……..11
3.4 Pengaruh Etnisitas
dalam pembentukan “nation and character building”………….….…12
BAB
IV PENUTUP
4.1
Kesimpulan……..………..……………………………………………………………..........15
DAFTAR
PUSTAKA …………………………..…..………..………………………………….16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Saat ini Indonesia berada di tengah era baru, yang dinamakan
era reformasi. Kondisi mengemuka sebagai
tantangan di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial
budayanya. Masalah-masalah kita sebagai bangsa memang kompleks, seiring dengan
makin berkembangnya dinamika zaman, seperti arus globalisasi yang demikian
mengalir secara deras dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa. Kebudayaan
Indonesia yang menjadi identitas etnis atau suku bangsa yang tadinya dianggap
mempunyai batas- batas yang jelaspun kini juga berubah. Perubahan ini berkaitan
dengan faktor geografis dan nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap
pengikat dalam membentuk masyarakat. Faktor geografis berkaitan dengan wilayah
geografis etnis yang tidak lagi terbatasi. Seperti orang Jawa yang ada di
Suriname atau orang Cina di Kalimantan. Batas-batas geografis itu tidak lagi
menjadi jelas karena tingkat mobilitas gerak orang sudah demikian meluas dan
intensifnya. Demikian pula dengan faktor nilai-nilai yang dibagi bersama
menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antar etnis, bahkan antar bangsa,
sesuai dengan konteks dan setting sosial yang berbeda.
Sementara itu, Prof HAR Tilaar yang
merupakan tokoh pendidikan nasional menilai, “Menjadi Indonesia itu memerlukan
waktu yang cukup panjang. Indonesia kita ini terdiri dari banyak suku bangsa
atau etnis, dari etnis inilah kita bersama-sama bertekad untuk membangun
Indonesia. Jadi, dasar dari Meng-Indonesia itu adalah Etnisitas yang
dikembangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” terangnya. Saat ini yang namanya
Indonesia itu masih belum dapat dicapai, tetapi kita masih dalam proses untuk
menjadi Indonesia. Oleh karena itu ‘Meng-Indonesia’ itu merupakan suatu proses
menjadi Indonesia yang di dalam sejarah perkembangan manusia, naik turun di
mana kadang kuat dan kadang melemah.
Konsep Indonesia sebagai bangsa,
yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang
relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat
rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu karena
dominasi pusat kepada daerah, yang kemudian berkembang menjadi dominasi suku
bangsa tertentu kepada suku bangsa yang lain. Rasa ketidakadilan ini kemudian
berujung kepada konflik-konflik sosial antar etnik (Parsudi Suparlan, 1999:
8-17). Rasa ketidakadilan tersebut memunculkan keinginan etnik-etnik tersebut
untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara
yang sama, yaitu Indonesia. Munculah Papua merdeka, Aceh Merdeka dan lain-lain.
1.2 Rumusan Masalah
A. Bagaimana
hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan?
B. Apakah
pengaruh barat dan kebudayaan Naional itu ?
C. Apakah
makna pengabdian itu ?
D. Bagaimana pengaruh Etnisitas itu
sendiri terhadap pembentukan “nation and character building”?
1.3 Tujuan
Tujuan
dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan diharapkan
bermanfaat bagi kita semua.
1.4 Sistematika
Makalah
A.
Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Prosedur pemecahan masalah
4. Sistematika Makalah
B.
Tinjauan
teoritis
1. Pengertian etnis, etnisasi dan ‘nation
and character building’
C.
Pembahasan
1. Pengaruh etnisitas terhadap
pembentukan “nation and character building” Indonesia.
2. Dampak globalisasi terhadap
etnisitas di Indonesia saat ini
3. Pengaruh etnisitas terhadap demokrasi di
Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
D.
Penutup
1. Kesimpulan
2. Saran
E.
Daftar
Pustaka
BAB
II
TINJAUAN
PUSTAKA
2.1 Pengertian etnis, etnisasi dan
‘nation and character building’
a)
Etnis
Dalam
Ensiklopedi Indonesia disebutkan istilah etnis atau etnik berarti kelompok
sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan
tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.
Schemerhon dalam Purwanto (2007)
mendefinisikan etnik sebagai kolektiva yang memiliki persamaan asal nenek
moyang, baik secara nyata maupun semu, memiliki pengalaman sejarah yang sama,
dan suatu kesamaan fokus budaya yang terpusat pada unsur-unsur simbolik yang
melambangkan persamaan ciri-ciri fenotipe, religi, bahasa, pola kekerabatan,
dan gabungan unsur-unsur itu.
b)
Etnisitas
Etnisitas
adalah suku bangsa, yakni berkaitan dengan kesadaran akan kesamaan tradisi
budaya, biologis, dan jati diri sebagai suatu kelompok (Tilaar, 2007:4-5) dalam
suatu masyarakat yang lebih luas.
c)
Nation and character building
Nation and
character building merupakan pembangunan karakter dan bangsa. Ernest Renan
berpendapat, nation atau bangsa ialah suatu solidaritas besar, yang terbentuk
karena adanya kesadaran akan pentingnya berkorban dan hidup bersama-sama di
tengah perbedaan, dan mereka dipersatukan oleh adanya visi bersama. Sedangkan
arti karakter itu sendiri berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi
‘positif’, bukan netral. Jadi, ‘orang berkarakter’ adalah orang punya kualitas
moral (tertentu) yang positif. Dengan demikian, pembangunan karakter, secara
implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau
berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif
atau yang buruk, khususnya disini bangsa yakni dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
BAB
III
PEMBAHASAN
3.1 Pengaruh Barat dan Kebudayaan
Nasional
Kebudayaan Barat
yang disebut kebudayaan modern itu bermula pada zaman Renaisance. Ketika Vasco
da Gama sebagai wakil kebudayaan Barat berhasil mengelilingi Afrika dan
mendarat di Kalikut, maka terbentanglah bagi seluruh Asia suatu sejarah baru.
Sejak itulah bangsa Eropa yang sudah modern itu berbondong-bondong datang ke
Asia dan secara perlahan-lahan membenamkan cengkeraman kuku penjajahnya, yamg
membuat sengsara bangsa-bangsa di benua ini, termasuk Indonesia. Bangsa-bangsa
Portugis, Inggris dan Belanda saling berdatangan ke Nusantara kita. Kedatangan
mereka yang semula berlatar belakang perdagangan itu kemudian berubah menjadi
penjajahan.
Bangsa
Belandalah yang dalam hal ini paling berperan. Karena kurang lebih 300 tahun
lamanya berhasil menancapkan kuku-kuku penjajahannya ke tubuh Indonesia. Kira-kira
pada abad ke 19 situasi mulai berubah ketika pemerintah Hindia-Belanda dengan
sedikit demi sedikit memberi kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk
bersekolah yaitu suatu cara belajar system barat yang belum pernah dikenal
sebelumnya. Kira-kira pada pertengahan abad 20 sejumlah pemuda Indonesia sudah
berhasil menghirup ilmu modern Barat itu melalui sistem pendidikan Belanda,
dari berbagai jurusan ilmu (misalnya kedokteran, teknik, hukum dan sebagainya). Mereka inilah yang bagaikan
senajata makan tuan kemudian membuka mata bangsa Indonesia akan haknya sebagai
manusia yang bebas, sehingga bangkit melawan penjajah dan akhirnya merdeka.
Pertemuan dengan
bangsa-bangsa Eropa telah memperkenalkan kepada kita unsur-unsur budaya sebagai
berikut : ilmu pengetahuan /tekhnologi, system sosial, system ekonomi,peralatan
bahasa Eropa, kesenian dan agama Kristen. Di samping itu mereka juga
memperkenalkan huruf dan tulisan latin yang merupakan unsur penting bagi
terbuka lebarnya komunikasi budaya Internasional. Memang tidak bisa dipungkiri
lagi bahwa kebudayaan barat besar sekali sumbangannya di bidang ilmu
pengetahuan /tekhnologi, system ekonomi, system demokrasi bagi masyarakat
Indonesia. Pengaruh kebudayaan barat sangat nyata dengan adanya proses
modernisasi kehidupan masyarakat kita.
System
pengetahuan dan tekhnologi serta ekonomi barat telah mampu memecahkan berbagai
problemasosial masyarakat di Eropa. Demikan juga hal yang sama pasti bisa
terapkan kepada masyarakat kita. Masyarakat Indonesia yang sudah ditakdirkan
hidup di tengah alam yang berkelimpahan ini, agaknya telah terbuai oleh karunia
tersebut.
Masyarakat yang
sudah dimanja oleh alam, akan lemah dalam juangnya, bila pada saatnya
menghadapi situasi yang sukar dan gawat, karena tidak terlatih untuk menghadapi
tantangan. Dalam kenyataan saat ini jelas alam kita tidak lagi begitu bermurah
dan bermanfaat kepada manusia Indonesia, berbeda situasinya dengan dahulu kala.
Kepadatan penduduk dan tidak baik proses eksploitasi alam menyebabkan
ketimpangan-ketimpangan. Menghadapi kenyataan ini, tidak bisa tidak kita harus
berani melepaskan diri dari buaian yang menjerumuskan itu, dan bangkit
mempersiapkan diri untuk menaklukan alam, demi mempertahankan hidup. Cara
satu-satunya ialah menguasai tekhnologi modern itu. Metode tradisional sudah
harus ditinggalkan karena tidak relevan dan tidak mampu lagi memecahkan masalah
kehidupan sosial ekonomi yang semakin menekan ini.
Sistem demokrasi
barat telah merpercepat bangsa kita
untuk menggalang solidaritas masyarakat terutama sesudah lepas dari penjajahan,
untuk menyusun sistem sosial dan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan
tuntutan zaman.
Penguasaan
bahasa Eropa oleh bangsa kita, memperluas hubungan kita dengan dunia
Internasional dan sekaligus membukas lebar kesempatan untuk ambil alih ilmu dan
teknologi modern itu. Jadi unsur yang menonjol dari kebudayaan barat itu adalah
sistem ilmu pengetahuan /tekhnologi,
sistem ekonominya.
Tekanan-tekanan
budaya barat terhadap budaya Indonesia sebelumnya, yaitu anasir asli, Hindu dan
Islam, memanglah cukup berat. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari
masyarakat belum mau demikian saja meninggalkan unsur kebudayaan
tradisionalnya. Mereka masih memadukan unsur-unsur modern dan tradisional. [[1]]
3.2 Hubungan antara manusia, masyarakat
dan kebudayaan
1) Hubungan manusia dengan masyarakat
Manusia hidupnya selalu di dalam masyarakat.
Hal ini bukan hanya sekedar ketentuan semata-mata, melainkan mempunyai arti
yang lebih dalam yaitu bahwa hidup bermasyarakat itu adalah rukun bagi manusia
agar benar-benar dapat mengembangkan budayannya dan mencapai kebudayaannya.
Tanpa masyarakat hidup manusia tidak dapat menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan.
Misalnya Casper Hauser yang berumur 18 tahun adalah anak yang diketemukan di
Neurenberg (Jerman) belum pernah hidup bermasyarakat. Ternyata setelah dibawa ke
dalam kehidupan masyarakat, ia tidak dapat berjalan dan berbahasa.
2) Hubungan manusia dengan kebudayaan
Dipandang dari sudut antropologi, manusia dapat
ditinjau dari 2 segi, yaitu
·
Manusia sebagai makhluk biologi
·
Manusia sebagai mkhluk sosio-budaya
Sebagai makhluk biologi, manusia dipelajari dalam
ilmu biologi atau anatomi dan sebagai makhluk sosio-budaya manusia dipelajari
dalam antropologi budaya. Antropologi
budaya manusia menyelidiki seluruh cara hidup manusia, bagaimana manusia dengan akal budinya dan struktur fisiknya
dapat mengubah lingkungan berdasarkan
pengalaman. Juga memahami, menuliskan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat
manusia.
Akhirnya terdapat suatu konsepsi tentang kebudayan
manusia yang menganalisis masalah-masalah hidup sosial-kebudayaan manusia.
Konsepsi tersebut ternyata memberi gambaran kepada kita bahwasannya hanya
manusialah yang mampu berkebudayaan. Sedangkan pada hewan tidak memiliki
kemampuan tersebut. Mengapa hanya manusia saja yang memiliki kebudayaan? Hal
ini dikarenakan manusia dapat belajar dan dapat memahami bahasa, yang
kesemuanya itu bersumber pada akal manusia.
Kesimpulannya: bahwa hanya manusialah yang dapat
menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia.
3) Hubungan masyarakat dengan
kebudayaan
Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam
suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang
mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.
Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh
kecakapan, pengetahuan-pengetahuan sehingga penimbunan (petandon) itu dalam
keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya. Memang kebudayaan itu bersifat
comulatif, bertimbun. Dapat diibaratkan: manusia adalah sumber kebudayaan, dan
masyarakat adalah danau besar, dimana air dari sumber-sumber itu mengalir dan
tertando. Manusia mengangsu/mengambil air dari danau itu. Maka dapatlah
dikatakan manusia itu “mengangsu apikulan warih” (ambil air berpikulan air),
sehingga tidaklah habis air dalam danau itu, melainkan bertambah banyak karena
selalu ditambah oleh orang yang mengangsu itu. Jadi erat sekali hubungan antara
masyarakat dengan kebudayaan. Kebudayaan tak mungkin timbul tanpa adanya
masyarakat, dan eksistensi masyarakat itu hanya dapat dimungkinkan oleh adanya
kebudayaan.
4) Hubungan manusia, masyarakat dan
kebudayaan
Dengan melihat uraian tersebut diatas, maka ternyata
manusia masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi
dipisahkan dalam artinya yang utuh. Karena ketiga unsur inilah kehidupan
makhluk sosial berlangsung.
Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pada manusia
karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat yaitu hidup bersama-sama
dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak.
Sebaliknya manusia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Seorang manusia
yang tidak pernah mengalami hidup bermasyarakat tidak dapat menunaikan
bakat-bakat manusianya yaitu mencapai kebudayaan. Dengan kata lain dimana orang
hidup bermasyarakat, pasti akan timbul kebudayaan.
Adanya kebudayaan didalam masyarakat itu merupakan
bantuan yang besar sekali pada individu-individu, baik sejak permulaan adanya
masyarakat sampai kini, didalam melatih dirinya memperoleh dunianya yang baru.
Dari setiap generasi manusia, tidak lagi memulai dan menggali yang baru, tetapi
menyempurnakan bahan-bahan lama menjadi yang baru dengan berbagai macam cara,
kemudian sebagai anggota generasi yang baru itu telah menjadi kewajiban
meneruskan kegenerasi selanjutnya segala apa yang mereka pelajari dari masa
lampau dan apa yang mereka sendiri telah tambahkan pada keseluruhan aspek
kebudayaan itu.
Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah
didalam bertindak dan berfikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang
fundamental, dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan
individu dan masyarakat. Dan akhirnya dimana manusia hidup bermasyarakat
disanalah ada kebudayaan, dan kesemuanya menjadi benda penyelidikan sosiologi.
3.3 Makna Pengabdian
Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa
pikiran,pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan antara lain kepada
raja, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan dan semua dilakukan dengan
ikhlas.
Timbulnya pengabdian itu hakikatnya ada rasa
tanggung jawab. Apabila kita bekerja dari pagi sampai sore hari di beberapa
tempat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, itu bearti pengabdi kepada
keluarga karena kasih sayang kita kepada keluarga.
Lain halnya jika keluarga kita membantu teman,
karena ada kesulitan, mungkin sampai berhari-hari ikut menyelesaikannya sampai
tuntas, ibu bukan pengabdian, tetapi hanya bantuan saja.
1.
Pengabdian
Kepada Keluarga
Pada
hakikatnya manusia hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga ini didasarkan atas
cinta dan kasih sayang. Kasih sayang ini mengandung pengertian pengabdian dan
pengorbanan. Tidak ada kasih sayang tanpa pengabdian. Bila ada kasih sayang
tidak disertai pengabdian, berarti kasih sayang itu palsu atau semu. Pengabdian
kepada keluarga ini dapat berupa pengabdian kepada istri dan anak-anak, istri
kepada suami dan anak-anaknya, atau anak-anak kepada orangtua.
2.
Pengabdian
kepada masyarakat
Manusia
adalah anggota masyarakat, ia tak dapat hidup tanpa orang lain, karena
tiap-tiap orang saling membutuhkan.Bila seseorang yang hidup di masyarakat
tidak mau memasyarakatkan diri dan selalu mengasingkan diri, maka apabila
mempunyai kesulitan yang luar biasa. Ia akan di tertawakan oleh masyarakat;
cepat atau lambat ia akan menyadari dan menyerah kepada masyarakat
lingkungannya.
Oleh
karena itu, demi masyarakat, anggota masyarakat harus mau mengabdi diri kepada
masyarakat. Ia harus mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh
karena nama baik tempat ia tinggal,membawa nama baiknya pula. Bila remaja
masyarakat kampungnya terkenal dengan ” remaja berandal “ suka berkelahi,
mengganggu orang, atau merampas hak orang lain maka bagaimana pun juga ia akan
merasa malu.
3.
Pengabdian
Kepada Negara
Manusia
pada hakikatnya adalah bagian dari suatu bangsa atau warga negara suatu negara.
Karena itu seseorang wajib mencintai bangsa dan negaranya. Mencintai ini
biasanya di wujudkan dalam bentuk pengabdian. Banyak contoh pengabdian kepada
bangsa dan negara dalam kehidupan.
4.
Pengabdian
Kepada Tuhan
Manusia
tidak ada dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai
ciptaan Tuhan manusia wajib mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian berarti
penyerahan diri sepenuhya kepada Tuhan, dan itu merupakan perwujudan tanggung
jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.[[2]]
v Dapat
disimpulkan bahwa :
Pengabdian
adalah perbuatan manusia baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga
sebagai perwujudan kesetian cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan dan
semua dilakukan secara ikhlas. Pengabdian pada dasarnya adalah rasa tanggung
jawab.
Manusia
hidup berkeluarga, karena itu manusia wajib mengabdi kepada keluarga, karena
anggota masyarakat, manusia wajib mengabdi kepada masyarakat. Manusia sebagai
anggota suatu bangsa dan warga negara suatu negara, wajib mengabdi kepada
bangsa dan negaranya. Karena manusia makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia wajib
mengabdi kepada Tuhan.
3.4 Pengaruh
Etnisitas terhadap pembentukan “nation and character building” Indonesia
Nasionalisme atau rasa dan tanggung jawab kebangsaan
tersebut merupakan sesuatu yang penting di dalam proses “character and nation
building”. Tidak ada bangsa hadir tanpa nasionalisme, tentu saja dengan kadar
dan konteks masing-masing, sesuai dengan histori dan banyak faktor yang
mempengaruhinya. Nasionalisme dan proses berbangsa, justru baru dimulai dan
memperoleh tantangan-tantangan baru setelah bangsa itu sendiri hadir, dengan
berbagai adat istiadat dan segala keunikannya yang dapat membentuk pembangunan
karakter bangsa Indonesia dengan ciri dan karakteristik yang milikinya, yang
tentunya tetap satu berbhineka tunggal ika. Kesadaran nasionalisme Indonesia
itu sendiri sebagai proses dalam mencapai pembangunan karakter bangsa tak lepas
dari era kebangkitan nasional 1908, dan Sumpah pemuda 1928 yang telah
meninggalkan dokumen amat mendasar sebagai wujud dari adanya kesamaan nasib dan
solidaritas bersama untuk bertanah air, bertumpah darah, dan berbahasa satu,
bahasa Indonesia. Jadi rasa meng-Indonesia tumbuh atas kesadaran bersama
segenap elemen yang ada untuk bersama-sama mewujudkan, memelihara dan memajukannya,
tanpa memandang etnis atau suku manapun, yang seharusnya itu semua menjadi satu
yakni pemersatu bangsa Indonesia. Indonesia hadir bukan atas pemberian kaum
penjajah. Ini suatu modal sejarah yang amat berharga.
Di
atas telah disinggung bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam
suku bangsa, etnisitas, bahasa, agama, dan adat-istiadat, yang satu sama lain
saling memperkaya bangunan kebangsaan yang plural dan kokoh. Dengan kata lain,
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Komposisi
keragaman dan kemajemukan bangsa merupakan suatu realitas objektif, yang
merupakan modal berharga bagi pembentukan jati diri dan karakter bangsa, yang
mana diikat pula oleh konsensus dasar Negara kita yaitu Pancasila.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ada pada saat
ini memiliki sejarah yang panjang, mengalami beberapa fase penjajahan bangsa
asing. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, para Bapak Bangsa (The Founding
Father’s) merumuskan konsepsi dasar yang tepat bagi kehadiran sebuah negara dan
bangsa baru bernama Indonesia. Sejak kemerdekaannya 17 Agustus 1945 hingga
kini, sesungguhnya bangsa Indonesia tengah berupaya untuk memperkokoh “nation
and character building”. Sebagai bangsa yang telah berusia setengah abad lebih,
Indonesia terus berproses dan berkembang seiring dengan “nation and character
building” tersebut. Selama ini bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang
harmonis, ramah, dan tingkat toleransi yang tinggi. Kesan demikian, khususnya
pada era reformasi tampak kian pudar, seiring dengan munculnya banyak konflik
sosial secara horisontal di kalangan masyarakat, dan banyaknya kerusuhan sosial
yang terjadi. Tentu saja berbagai kejadian yang muncul tersebut menodai proses
“nation and character building”. Kini saatnya bangsa Indonesia menunjukkan
kembali karakternya sebagai bangsa yang ber-Pancasila dan bermartabat.
Betapapun kompleksnya tantangan yang kita hadapi, kita harus
tetap mencintai bangsa ini. Bangsa di mana kita dilahirkan dan dibesarkan,
dengan berbagai macam etnis didalamnya yang tentunya dapat menjadi pengaruh
positif bagi pembentukan pembangunan karakter bangsa disertai satu bahasa
nasional, satu dasar Negara yaitu Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa, yang
memberikan harapan akan masa depan bagi kita semua, bangsa Indonesia. Dan kita
pun harus mengembangkan rasa tanggung jawab, di samping secara mendasar kita
harus memahami hakikat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki
nilai-nilai dasar (basic values) Pancasila, sebagai karakter bangsa Indonesia
yang diharapkan, yakni bangsa yang:
1)
Ber-Ketuhanan
yang Maha esa
2)
Ber-Kemanusiaan
yang adil dan beradab
3)
Senantiasa
berada dalam Persatuan Indonesia
4)
Melaksanakan
Permusyawaratan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5)
Mewujudkan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Inilah konsensus dasar kita
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Etnisitas dalam konteks Indonesia akan dapat berperan
penting di dalam pembentukan karakter pembangunan bangsa. Hal-hal di atas
adalah realitas-realitas obyektif atau kenyataan-kenyataan yang tidak dapat
dipungkiri, bahwa Indonesia adalah negara besar dan plural. Besar karena,
wilayahnya yang amat luas dan jumlah penduduknya yang demikian banyak. Plural,
karena kenekaragaman budaya (suku/etnis, ras, adat-istiadat, bahasa dan agama).
Faktor etnisitas tadi jika ditransformasikan secara produktif, akan
menyumbangkan pertumbuhan kehidupan demokrasi yang baik dan menjadi ciri
karakteristik bangsa dengan berbagai budayanya yang ada,namun tetap berbhineka
tunggal ika. Tetapi juga sebaliknya bisa memicu konflik jika setiap kelompok
gagal membangun sikap solidaritas sebagai warga Negara dan bangsa
(nation-state).
BAB
IV
PENUTUP
4.1
KESIMPULAN
Pada pertengahan
abad 20 sejumlah pemuda Indonesia sudah berhasil menghirup ilmu modern Barat
itu melalui sistem pendidikan Belanda, dari berbagai jurusan ilmu (misalnya
kedokteran, teknik, hukum dan
sebagainya). Mereka inilah yang bagaikan senajata makan tuan kemudian membuka
mata bangsa Indonesia akan haknya sebagai manusia yang bebas, sehingga bangkit
melawan penjajah dan akhirnya merdeka.
Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah
didalam bertindak dan berfikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang
fundamental, dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan
individu dan masyarakat. Dan akhirnya dimana manusia hidup bermasyarakat
disanalah ada kebudayaan, dan kesemuanya menjadi benda penyelidikan sosiologi.
Pengabdian adalah perbuatan manusia baik yang berupa
pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetian cinta, kasih
sayang, hormat, atau suatu ikatan dan semua dilakukan secara ikhlas. Pengabdian
pada dasarnya adalah rasa tanggung jawab. Manusia hidup berkeluarga, karena itu
manusia wajib mengabdi kepada keluarga, karena anggota masyarakat, manusia
wajib mengabdi kepada masyarakat. Manusia sebagai anggota suatu bangsa dan
warga negara suatu negara, wajib mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Karena
manusia makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia wajib mengabdi kepada Tuhan.
Etnisitas
tentunya dapat berperan penting di dalam pembentukan karakter pembangunan
bangsa. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia adalah negara
besar dan plural. Besar karena, wilayahnya yang amat luas dan jumlah
penduduknya yang demikian banyak. Plural, karena kenekaragaman budaya
(suku/etnis, ras, adat-istiadat, bahasa dan agama). Faktor etnisitas jika
ditransformasikan secara produktif, akan menyumbangkan pertumbuhan kehidupan demokrasi
yang baik dan menjadi ciri karakteristik bangsa dengan berbagai budayanya yang
ada,namun tetap berbhineka tunggal ika. Tetapi juga sebaliknya bisa memicu
konflik jika setiap kelompok gagal membangun sikap solidaritas sebagai warga
Negara dan bangsa (nation-state).
DAFTAR PUSTAKA
·
Suryadi
M.P, Drs. Buku Materi Pokok Ilmu Budaya
Dasar, Depdikbud UT, Buku I – II, 1985
·
Suprihadi
Sastrosupon, M., Ilmu Budaya Dasar,
UKSW, Salatiga, 1987
·
http://riezaarif.blogspot.com/2010/04/etnisitas-dalam-pembentukan-nation-and.html
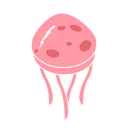
No comments:
Post a Comment